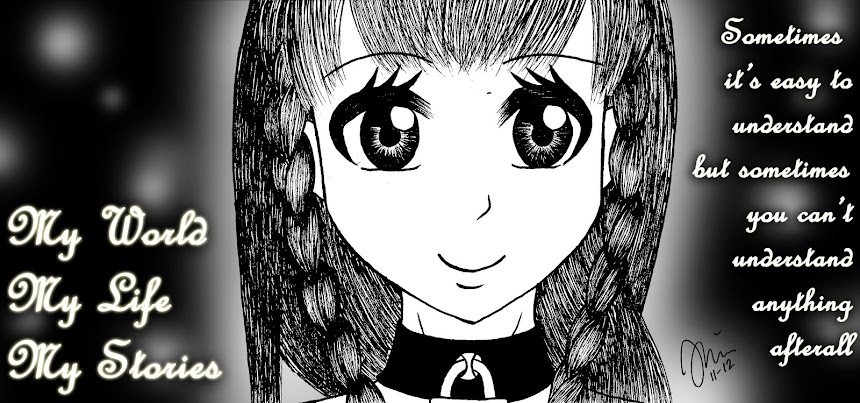Minggu, 20 Januari 2013
Sabtu, 29 Desember 2012
Kamis, 27 Desember 2012
The Undone Story I made back in... 2009 I guess?
“The Secrets of
Kevin Sandler”
One : Secrets Unrevealed
Tokyo, Jepang, 04 : 23 …
Sebuah pesawat kecil mendarat di
Bandara Internasional Narita.
“Hmm… Aku kangen tempat ini…” kata
seorang cowok yang kira-kira berumur dua puluh tahunan itu sambil turun dari
pesawat.
“Ingat Kevin, kita disini untuk
tugas. Bukan untuk liburan.” Tukas pria bertubuh besar dibelakangnya. Cowok
yang tadi dipanggil Kevin berhenti mendadak dan membalikkan badannya.
“Yo, aku tahu itu, botak! Y’don’t
have to be so cruel y’know?!” Ujar Kevin dengan gaya Hip Hop. Setelah itu dia berbalik lagi
dan meneriakkan kata-kata yang asing bagi pria botak tadi.
“Bahasa apa yang dia pakai?” bisik
pria botak itu kepada seseorang di belakangnya.
“Bahasa Jepang, pak.”
“Apa dia mengejekku?”
“Tidak, pak.”
“Hmph… Dasar anak muda.” Gumam pria
botak itu.
~###~
Pusat
kota Tokyo, 07 : 15 …
Tokyo di pagi hari, tak terbayang sibuknya
orang berlalu lalang untuk segera memulai aktivitas mereka. Tapi dibalik
kesibukan itu, tak ada yang menyadari keberadaan seorang cowok berambut
kemerahan yang sedang melompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Cuaca yang
cerah justru membuatnya sulit dilihat karena dia memakai pakaian serbaputih.
Cowok itu berhenti di satu gedung yang cukup tinggi, kemudian mengambil
binocular (semacam teropong tapi lebih canggih :) dan mengobservasi gedung
raksasa yang ada di depannya.
“Cuaca cerah dan target ada di
lokasi. Semua sesuai rencana.” Batinnya.
Dia langsung memasukkan binocular
itu dan mengambil grappling hook (senjata yang melemparkan pengait) dari
ranselnya dan menembakkannya kea rah lantai 49 gedung tersebut. Dia
menggunakannya untuk masuk ke gedung itu. Semua dia lakukan dengan cepat, tak
ada satupun yang melihatnya. Setelah menyelesaikan urusannya di lantai 49, dia
segera naik ke lantai 50, lantai paling atas tempat target berada.
Begitu sampai di kantor si target,
dia langsung menodongkan pistol semi-automatisnya pada sebuah kursi yang
membelakanginya.
“Maaf, Yamada-san. Bisnismu berakhir
di sini.” Katanya sambil menarik pelatuk pistolnya. Tapi dia kaget karena si
target dapat menghindari tembakannya dengan gaya acrobat yang luar biasa. Padahal di
profil si target tak ada tulisan yang membahas kalau dia bisa melakukan
acrobat!
“Yo~ salah orang!!” Ternyata orang
itu adalah Kevin.
“Kevin Sandler?!” Cowok berambut
kemerahan tadi geram melihat Kevin.
“Red Poison, ‘kan? Kita pernah bertemu…” sambut Kevin.
Meraka saling bertatapan. Mereka
saling kenal satu sama lain karena pernah bertemu sebelumnya. Pertemuan yang
sama seperti ini. Pertemuan yang mengharuskan mereka untuk bertarung.
Kevin Sandler, anggota tim White
Eagle yang biasa disewa untuk melawan pembunuh bayaran level tinggi.
Red Poison, salah satu pembunuh
bayaran yang sangat popular. Anggota organisasi Bloody Tears, organisasi
pembunuh bayaran yang cukup besar.
“Mungkin kemarin aku kalah darimu,
tapi kali ini…” Red Poison tidak melanjutkan perkataannya, ia langsung
mengambil sebuah senapan otomatis dari dalam ranselnya.
“… Kali ini akulah yang akan menang!”
Lanjutnya dengan percaya diri dan menghujani lawannya dengan serentetan peluru.
Kevin yang sudah siap menghindari
tembakan itu dengan bersalto ke kiri, bersembunyi di balik lemari kayu yang
lumayan besar. Kemudian dia mengeluarkan Dual Elite-nya dan bersiap untuk
menyerang balik!
~###~
Sementara
itu…
Eriko membuka laptopnya. Tak ada
E-mail baru. Dia sedang menunggu E-mail dari temannya yang sedang ada di luar kota, namanya Rei. Rei
adalah teman masa kecilnya. Saat kakaknya meninggal, Rei-lah yang menghiburnya.
Tapi dia tidak membalas E-mail Eriko sejak tiga bulan lalu. Eriko memutuskan
untuk turun dan melahap sarapannya.
“Ohayo,
Ibu.” Tuturnya menyapa ibunya.
“ah, Ohayo. Kamu sudah bangun ya?” Balas ibunya dengan senyum ramah.
Eriko memberikan jawabannya dengan anggukan.
“ah, Eriko. Hari ini kamu berangkat
pakai mobil saja ya?”
“he? Kenapa?” Tanya Eriko.
“yaa… Nggak papa. Bukannya kamu
senang? Lagipula temanmu Hikari mau minta diantarkan.”
“ooh.. Baiklah kalau begitu.”
~###~
Kembali
ke pertarungan yang tadi.
Kantor yang tadinya rapi tertata
menjadi hancur berantakan dalam sekejap karena hujan peluru yang dilepaskan
Kevin dan Red Poison. Meskipun begitu, belum ada satu peluru pun yang menembus
kulit mereka.
“Kevin,
lapor status.” Perintah seseorang di komunikator Kevin.
“Sibuk, yo!” jawabnya.
“Target
aman bersamaku.”
“Aku nggak nanya, botak!”
“Butuh
bantuan?”
“Nggak.”
“Aku
akan tetap datang.”
“AKH!”
“Kevin?!”
Akhirnya sebuah tembakan Red Poison
sukses mengenai paha kanannya. Ia berusaha untuk tidak bersuara, lawan tidak
boleh tahu kalau ia sedang terluka saat ini. Ia lalu berlari keluar kantor itu.
Red Poison mengikuti di belakangnya, lalu ia tersenyum melihat ada bercak darah
di lantai.
“Kevin?
Ada apa?” Komunikator
Kevin berbunyi lagi.
“Kantor itu terlalu sempit. Aku
butuh ruang gerak yang lebih luas! Pastikan lantai 49 kosong!”
“Aku
akan datang untuk membantumu.”
“Grrr… Tidak usah!” Kevin membuang
komunikatornya. Ia masuk ke sebuah kantor lain yang kosong dan bersembunyi di
balik meja. Tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing dan pandangannya sedikit
memudar. Ia baru sadar satu hal ;
‘Racun! Pasti ia menaruh racun Dalam
pelurunya tadi!’ batin Kevin. Kevin menyesal tidak menyadari ini lebih awal, ia
juga menyesal sudah menolak bantuan dari temannya. Baru saja ia berdiri untuk
mencari komunikator yang tadi dia buang, sosok Red Poison sudah muncul di hadapannya!
“Bagaimana? Sudah pusing?” Tanya Red
Poison dengan nada meremahkan. Kevin langsung melepaskan tembakan ke arahnya, tapi
Red Poison dapat menghindar dengan mudah! Kepala Kevin juga semakin pusing,
tanpa dia sadari dua keeping peluru sudah bersarang di betis kirinya,
membuatnya jatuh telungkup.
Red Poison berjalan mendekat, ia
menatap Kevin penuh kebencian
“Sayonara.” Gumamnya. Kemudian ia
mengarahkan pistolnya ke kepala Kevin dan…
KLIK KLIK!
Ternyata pelurunya habis! Kesempatan
ini digunakan dengan baik oleh Kevin, Tenaga yang tersisa ia gunakan untuk
menendang kaki Red Poison hingga jatuh dan berbalik menodongkan pistolnya ke
arah Red Poison.
“Hh… Lakukanlah… Bunuh aku
SEKARANG!”
Kevin tersenyum dan mendaratkan
peluru kea rah tangan dan kaki Red Poison.
“AAAKH!
Kenapa tidak langsung kau bunuh saja aku?”
“Aku
nggak bakal pernah membunuh…” Ujar Kevin lalu meninggalkan Red Poison di
tempatnya.
“Hmm…
jadi begitukah permainanmu?” Kata Red Poison sambil tersenyum kecil.
“Apa?”
“Aku
juga ada permainan…” Lanjutnya sambil berusaha berdiri.
“Apa
yang sedang kau rencanakan?” Tanya Kevin.
“Dalam
Sembilan… ah tidak, delapan menit lagi tempat ini akan meledak.” Katanya sambil
menyunggingkan senyum di bibirnya.
“Apa?
Kau menanam bom?!” Tanyanya lagi. Red Poison diam saja.
“KEPARAT
KAU!!” Kesal Kevin sambil menonjok Red Poison hingga jatuh.
“Kau
membuang waktumu, Kevin… 7 menit lagi…”
“Dimana
kau menanamnya?!”
“Entahlah…
Di sekitar lantai 49?” Jawabnya. Tanpa membuang waktu, Kevin berlari ke lantai
bawah.
~###~
Kevin
sudah mencari kemana-mana, tapi ia belum menemukan bomnya. Tepat saat ia
merencanakan untuk pergi, Ia menemukan satu titik bercahaya merah. Itulah
bomnya! Tapi ia sudah terlambat, waktunya tinggal 5 detik untuk meninggalkan
gedung itu!
00:05:00
Dia
berlari dan terus berlari, dia tak ingin menyia-nyiakan hidupnya disini..
00:04:00
Masih
banyak yang ingin dia lakukan…
00:03:00
Termasuk…
00:02:00
Bertemu
dengan dia…
00:01:00
BOOM!!!
~###~
“Kyaaaaa!
REM! REM!” Teriak Hikari di belakang.
CKIIIIIIT!
“Astaga,
suara apa itu tadi?” Tanya Eriko yang sedang menyetir.
“Kamu
dengar ‘kan?”
Lanjut Eriko, mengalihkan pandangannya ke belakang.
“Iya!
Tapi kamunya juga nggak usah sampai hilang kendali gitu, dong! Bisa mati
orang!” Hikari berusaha mengatur napasnya. Eriko tertawa kecil lalu melihat ke
depan lagi.
“Astaga…”
gumam Eriko hampir tak terdengar, tapi sampai ke telinga Hikari.
“Ada apa?” Tanya Hikari.
Eriko tak menjawab, ia seperti orang yang sedang dihipnotis, terus melihat ke
depan.
“Eriko?”
Tanyanya lagi. Lalu ia melihat kearah yang sama dengan Eriko.
“What
the…”
Mereka
tak bisa menjelaskan pemandangan yang mereka lihat. Sebuah gedung raksasa yang
bagian atasnya terbakar…
To be Continued
Jumat, 09 November 2012
~ Secret Thought ~ _chapitre 2, la confession_
Chapter 2 of Secret Thought! Enjoy~
la confession de l'amour...
Remillia berjalan melewati gerombolan penggosip tadi. Tangannya kanannya menggenggam cutter yang disembunyikan dalam kantongnya.
"De Javu" bisiknya.
***
"ugh..." Remillia mati-matian berusaha meraih buku yang ada di bagian paling atas rak. Kemudian sebuah tangan muncul meraih buku itu.
Luke Sieghart.
"yang ini?" tanyanya.
Remillia menatap buku itu cukup lama, kemudian menerimanya dengan tangan kanan.
"sebenarnya bukan yang ini."
"Nah lho?! Salah tapi kok diterima? Hahaha. Berarti yang ini ya?" Luke meraih buku satunya yang cukup tebal.
"kamu tak perlu repot mengurusiku. Aku bisa sendiri." tutur Remillia yang mendekap buku tadi dengan tangan kanannya.
"kan kemarin aku sudah bilang kamu nggak perlu menanggung semuanya sendiri." Luke tersenyum.
Ah, lagi-lagi tatapan itu. Tatapan Remillia yang datar, namun sangat emosional. Lagi-lagi Luke terbawa ombak biru kehitaman itu.
"ehm. Pasti yang ini kan?" Luke akhirnya menyerahkan buku itu. Remillia mengangguk, kemudian mengulurkan tangan kirinya untuk menerima buku itu. Namun belum berapa detik ia menggenggam buku itu, ia menjatuhkan buku itu.
"Remillia!"
Gadis itu jatuh terduduk diatas lantai dengan tangan kanan memegangi lengan kiri bawahnya.
"kenapa? Ada yang luka?" Luke duduk menjongkok dan meraih tangan kiri gadis itu.
"lepas!!" Remillia tiba-tiba menjerit dan menarik tangannya.
"aku hanya berusaha membantu! Aku ini anak PMR, perlihatkan lukanya percaya saja padaku." ucap Luke.
"tidak!! Aku tidak butuh! Cepat pergi, atau aku akan..."
"Akan apa?! Membunuhku dengan cutter itu?!" Remillia tersentak mendengar ucapan Luke. Luke pun refleks menutup mulutnya.
"maaf... Aku kelepasan..."
"ukh... teganya kau... Aku tidak menggunakannya untuk hal seperti itu..." mata Remillia berkaca-kaca.
"maaf... Hanya saja, hampir semua orang membicarakannya. Aku hanya..."
"seharusnya... Aku sudah berhenti melakukannya. Seharusnya... Tapi, kemarin... Ukh... Ungg..." air mata gadis itu pun tumpah juga. Jantung Luke seperti tersayat melihatnya.
"Remillia..." desah Luke.
"uh... baiklah... Aku percaya padamu Luke..." Remillia perlahan menggulung lengan baju kirinya.
Mata Luke terbelalak melihatnya. Terlalu banyak... Luka bekas sayatan. Kemudian luke membuka perban yang sudah bebercak darah. Ia melihat beberapa sayatan kecil yang masih terbuka dan sebuah sayatan besar menganga.
"Remillia... Ini..."
"seharusnya aku sudah berhenti melakukan ini... Tapi air mata saja tak cukup untuk semua kekesalan ini. Terhadap dunia, terhadap diriku yang lemah ini. Aku selalu puas meliat cairan merah itu mengalir, seakan kebencianku merambat keluar dari diriku. Sakit, tapi menyenangkan." Remillia tersenyum. Senyum paling menyeramkan yang pernah Luke lihat.
"ahaha, tapi sepertinya semalam aku terlalu bersemangat. Hingga lukanya jadi sedalam ini, ugh... Mungkin, kalau sedikit dalam lagi, nadiku akan terpo-"
"jangan melakukan hal bodoh!!" Luke meraih tangan kiri Remillia. Pandangan mereka bertubrukan.
Sunyi. Bahkan air mata Remillia berhenti mengalir. Hanya waktu yang terus berlalu.
TING TONG!
"bel masuk... Ayo kita ke UKS dulu." Luke berdiri, masih menggenggam tangan Remillia. Gadis itu juga berdiri lalu menurunkan gulungan lengannya.
Sambil berjalan ke UKS, Luke teringat sebuah novel yang pernah ia baca.
Cutter... 'cutter'... Dua kata yang homograf dan homofon, beda arti namun saling berkaitan... 'cutter', orang yang senang menyayat dirinya sendiri. Masochist. Dan Remillia adalah 'cutter' yang menggunakan cutter sebagai alatnya...
Angin tak berhembus, namun Luke merasakan hembusan sendu yang menerbangkan jiwanya, jauh dari tubuhnya...
***
"Remillia membawa cutter untuk melukai dirinya sendiri?" Bu Anne memastikan apa yang barusan ia dengar. Luke mengangguk.
"sepertinya ibu memang harus menemui orangtuanya."
"tapi ibu tahu kan, Remillia-"
"ya, ibu tahu kalau ia tidak mau ibu pergi. Tapi kalau masalahnya sudah sampai ke tingkat ini, orangtuanya harus tahu." Ibu Anne memperkuat argumennya.
"ibu memang benar, hanya saja aku..."
"Luke, seberapa jauh kau mengenal Remillia?" tanya bu Anne.
"hah? Uuh... Cukup jauh... Karena dia memberitahukan tentang luka itu padaku."
"hmm... Apa kau diberitahu bahwa ibunya meninggal 2 bulan lalu?"
Luke tersentak.
"apa kau diberitahu kalau di sekolah sebelumnya ia di-bully?"
"eh..."
"teman-temannya melukainya jasmani dan rohani. Menusuk lengannya dengan pensil, memukulnya dengan papan hingga tulang rusuknya retak. Kau tahu?"
Luke terdiam.
"Remillia layaknya gunung api di tengah lautan. Yang terlihat hanya puncaknya, namun jika kita menyelam, barulah terlihat kalau gunung itu sangatlah besar. Bagaimana kalau gunung itu meledak? Remillia butuh perlakuan khusus, jiwanya terguncang. Terapi, konsultasi psikologi. Karena itu orangtuanya harus tahu."
***
Luke merasa seperti tersambar petir. Berjalan keluar ruangan Bu Anne dengan lemas. Pikirannya mengantarkan langkahnya menemui Remillia di gerbang sekolah.
"Luke..."
Luke menoleh, dan tersenyum ke arah gadis di hadapannya.
"Claire."
"namaku Clarissa... Luke, kau menunggui gadis itu?" Luke tidak menjawab, "sadarlah Luke, dia itu psycho!"
"ssst." Luke menempelkan jari telunjuknya pada bibirnya, kemudian menunjuk ke belakang Clarissa. Clarissa menoleh dan terkejut saat melihat sosok Remillia ada di hadapannya. Remillia hanya diam menatap Clarissa. Tatapan yang kosong, tanpa emosi, namun tersirat aura dendam di dalamnya. Bibir Clarissa bergetar dan keningnya berkerut.
"Remillia, kau mau pulang?" tanya Luke. Remillia tidak mengacuhkan dua orang itu dan tetap berjalan melewati mereka. Luke juga tanpa bicara membuntuti Remillia.Mereka berjalan cukup jauh tanpa kata-kata. Dan akhirnya Remillia berhenti lalu bertanya, "sampai kapan kau akan mengikutiku?"
"sampai kau mau mendengarkanku." jawab Luke tegas.
Remillia menghela napas dalam lalu berbalik ke arah Luke dan menunjukkan ekspresi yang seolah berkata, 'baiklah, aku mendengarkan.'
"kamu tahu? Aku masih menginginkannya. Kamu dan aku, rendezvous."
"kamu masih bersikeras? Padahal sudah kukatakan aku sibuk."
"ya. meskipun begitu, Nous allons à la bibliothèque." Luke tersenyum hangat saat mengatakannya. Remillia yang mendengarnya terdiam.
"bukankah kau bilang, kau hanya tahu kata 'rendezvous'?" Remillia terheran-heran.
"yah... Tapi aku berusaha belajar. Buat kamu." Luke menggaruk kepalanya.
"hah? Apa maksudnya untukku?" Remillia benar-benar kehilangan aura misteriusnya hari ini.
"supaya aku bisa bicara denganmu tanpa bingung." Luke berjalan mendekat kepada Remillia yang sedang terbengong-bengong. Semilir angin menjatuhkan dedaunan kering dari pepohonan di sekitar mereka. Kesunyian yang menyegarkan, menerbangkan perasaan Luke, jauh dari tubuhnya saat ini.
"kamu mau tahu kata lain yang sudah aku pelajari?" tanya Luke memecah kesunyian.
"... Je t'aime."
...
Terlantun dengan sangat jelas. Ungkapan cinta dalam bahasa Prancis itu bergema dalam gendang telinga mereka berdua. Diiringi dengan bisikan angin dan degupan jantung mereka, menciptakan melodi yang sulit dilupakan...
_bersambung-->ch.3_
la confession de l'amour...
Remillia berjalan melewati gerombolan penggosip tadi. Tangannya kanannya menggenggam cutter yang disembunyikan dalam kantongnya.
"De Javu" bisiknya.
***
"ugh..." Remillia mati-matian berusaha meraih buku yang ada di bagian paling atas rak. Kemudian sebuah tangan muncul meraih buku itu.
Luke Sieghart.
"yang ini?" tanyanya.
Remillia menatap buku itu cukup lama, kemudian menerimanya dengan tangan kanan.
"sebenarnya bukan yang ini."
"Nah lho?! Salah tapi kok diterima? Hahaha. Berarti yang ini ya?" Luke meraih buku satunya yang cukup tebal.
"kamu tak perlu repot mengurusiku. Aku bisa sendiri." tutur Remillia yang mendekap buku tadi dengan tangan kanannya.
"kan kemarin aku sudah bilang kamu nggak perlu menanggung semuanya sendiri." Luke tersenyum.
Ah, lagi-lagi tatapan itu. Tatapan Remillia yang datar, namun sangat emosional. Lagi-lagi Luke terbawa ombak biru kehitaman itu.
"ehm. Pasti yang ini kan?" Luke akhirnya menyerahkan buku itu. Remillia mengangguk, kemudian mengulurkan tangan kirinya untuk menerima buku itu. Namun belum berapa detik ia menggenggam buku itu, ia menjatuhkan buku itu.
"Remillia!"
Gadis itu jatuh terduduk diatas lantai dengan tangan kanan memegangi lengan kiri bawahnya.
"kenapa? Ada yang luka?" Luke duduk menjongkok dan meraih tangan kiri gadis itu.
"lepas!!" Remillia tiba-tiba menjerit dan menarik tangannya.
"aku hanya berusaha membantu! Aku ini anak PMR, perlihatkan lukanya percaya saja padaku." ucap Luke.
"tidak!! Aku tidak butuh! Cepat pergi, atau aku akan..."
"Akan apa?! Membunuhku dengan cutter itu?!" Remillia tersentak mendengar ucapan Luke. Luke pun refleks menutup mulutnya.
"maaf... Aku kelepasan..."
"ukh... teganya kau... Aku tidak menggunakannya untuk hal seperti itu..." mata Remillia berkaca-kaca.
"maaf... Hanya saja, hampir semua orang membicarakannya. Aku hanya..."
"seharusnya... Aku sudah berhenti melakukannya. Seharusnya... Tapi, kemarin... Ukh... Ungg..." air mata gadis itu pun tumpah juga. Jantung Luke seperti tersayat melihatnya.
"Remillia..." desah Luke.
"uh... baiklah... Aku percaya padamu Luke..." Remillia perlahan menggulung lengan baju kirinya.
Mata Luke terbelalak melihatnya. Terlalu banyak... Luka bekas sayatan. Kemudian luke membuka perban yang sudah bebercak darah. Ia melihat beberapa sayatan kecil yang masih terbuka dan sebuah sayatan besar menganga.
"Remillia... Ini..."
"seharusnya aku sudah berhenti melakukan ini... Tapi air mata saja tak cukup untuk semua kekesalan ini. Terhadap dunia, terhadap diriku yang lemah ini. Aku selalu puas meliat cairan merah itu mengalir, seakan kebencianku merambat keluar dari diriku. Sakit, tapi menyenangkan." Remillia tersenyum. Senyum paling menyeramkan yang pernah Luke lihat.
"ahaha, tapi sepertinya semalam aku terlalu bersemangat. Hingga lukanya jadi sedalam ini, ugh... Mungkin, kalau sedikit dalam lagi, nadiku akan terpo-"
"jangan melakukan hal bodoh!!" Luke meraih tangan kiri Remillia. Pandangan mereka bertubrukan.
Sunyi. Bahkan air mata Remillia berhenti mengalir. Hanya waktu yang terus berlalu.
TING TONG!
"bel masuk... Ayo kita ke UKS dulu." Luke berdiri, masih menggenggam tangan Remillia. Gadis itu juga berdiri lalu menurunkan gulungan lengannya.
Sambil berjalan ke UKS, Luke teringat sebuah novel yang pernah ia baca.
Cutter... 'cutter'... Dua kata yang homograf dan homofon, beda arti namun saling berkaitan... 'cutter', orang yang senang menyayat dirinya sendiri. Masochist. Dan Remillia adalah 'cutter' yang menggunakan cutter sebagai alatnya...
Angin tak berhembus, namun Luke merasakan hembusan sendu yang menerbangkan jiwanya, jauh dari tubuhnya...
***
"Remillia membawa cutter untuk melukai dirinya sendiri?" Bu Anne memastikan apa yang barusan ia dengar. Luke mengangguk.
"sepertinya ibu memang harus menemui orangtuanya."
"tapi ibu tahu kan, Remillia-"
"ya, ibu tahu kalau ia tidak mau ibu pergi. Tapi kalau masalahnya sudah sampai ke tingkat ini, orangtuanya harus tahu." Ibu Anne memperkuat argumennya.
"ibu memang benar, hanya saja aku..."
"Luke, seberapa jauh kau mengenal Remillia?" tanya bu Anne.
"hah? Uuh... Cukup jauh... Karena dia memberitahukan tentang luka itu padaku."
"hmm... Apa kau diberitahu bahwa ibunya meninggal 2 bulan lalu?"
Luke tersentak.
"apa kau diberitahu kalau di sekolah sebelumnya ia di-bully?"
"eh..."
"teman-temannya melukainya jasmani dan rohani. Menusuk lengannya dengan pensil, memukulnya dengan papan hingga tulang rusuknya retak. Kau tahu?"
Luke terdiam.
"Remillia layaknya gunung api di tengah lautan. Yang terlihat hanya puncaknya, namun jika kita menyelam, barulah terlihat kalau gunung itu sangatlah besar. Bagaimana kalau gunung itu meledak? Remillia butuh perlakuan khusus, jiwanya terguncang. Terapi, konsultasi psikologi. Karena itu orangtuanya harus tahu."
***
Luke merasa seperti tersambar petir. Berjalan keluar ruangan Bu Anne dengan lemas. Pikirannya mengantarkan langkahnya menemui Remillia di gerbang sekolah.
"Luke..."
Luke menoleh, dan tersenyum ke arah gadis di hadapannya.
"Claire."
"namaku Clarissa... Luke, kau menunggui gadis itu?" Luke tidak menjawab, "sadarlah Luke, dia itu psycho!"
"ssst." Luke menempelkan jari telunjuknya pada bibirnya, kemudian menunjuk ke belakang Clarissa. Clarissa menoleh dan terkejut saat melihat sosok Remillia ada di hadapannya. Remillia hanya diam menatap Clarissa. Tatapan yang kosong, tanpa emosi, namun tersirat aura dendam di dalamnya. Bibir Clarissa bergetar dan keningnya berkerut.
"Remillia, kau mau pulang?" tanya Luke. Remillia tidak mengacuhkan dua orang itu dan tetap berjalan melewati mereka. Luke juga tanpa bicara membuntuti Remillia.Mereka berjalan cukup jauh tanpa kata-kata. Dan akhirnya Remillia berhenti lalu bertanya, "sampai kapan kau akan mengikutiku?"
"sampai kau mau mendengarkanku." jawab Luke tegas.
Remillia menghela napas dalam lalu berbalik ke arah Luke dan menunjukkan ekspresi yang seolah berkata, 'baiklah, aku mendengarkan.'
"kamu tahu? Aku masih menginginkannya. Kamu dan aku, rendezvous."
"kamu masih bersikeras? Padahal sudah kukatakan aku sibuk."
"ya. meskipun begitu, Nous allons à la bibliothèque." Luke tersenyum hangat saat mengatakannya. Remillia yang mendengarnya terdiam.
"bukankah kau bilang, kau hanya tahu kata 'rendezvous'?" Remillia terheran-heran.
"yah... Tapi aku berusaha belajar. Buat kamu." Luke menggaruk kepalanya.
"hah? Apa maksudnya untukku?" Remillia benar-benar kehilangan aura misteriusnya hari ini.
"supaya aku bisa bicara denganmu tanpa bingung." Luke berjalan mendekat kepada Remillia yang sedang terbengong-bengong. Semilir angin menjatuhkan dedaunan kering dari pepohonan di sekitar mereka. Kesunyian yang menyegarkan, menerbangkan perasaan Luke, jauh dari tubuhnya saat ini.
"kamu mau tahu kata lain yang sudah aku pelajari?" tanya Luke memecah kesunyian.
"... Je t'aime."
...
Terlantun dengan sangat jelas. Ungkapan cinta dalam bahasa Prancis itu bergema dalam gendang telinga mereka berdua. Diiringi dengan bisikan angin dan degupan jantung mereka, menciptakan melodi yang sulit dilupakan...
_bersambung-->ch.3_
Memoria ~ Melodi yang tak Terlupakan ~
Halooo~ Ini cerita yang (rencananya) mau kukirim buat lomba nulis cerpen! Enjoy~
“Memoria”
~ Melodi yang
Tak Terlupakan ~
“Rasanya seperti melangkah di atas pasir di pinggir pantai. Jejakmu
akan terhapus begitu ombak datang menerjang…”
* * *
“Selamat
pagi”
Bisikan
lembut yang asing merambat di telinganya, seiring dengan semilir angin yang
membelai pipinya. Wangi teh melati pun samar-samar tercium. Wanita itu membuka
matanya, dan ia melihat jendela yang telah terbuka dengan korden putih berdansa
bersama hembusan angin. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dan yang ia lihat
sebuah ruangan serba putih yang asing. Tidak begitu sempit dan tidak begitu
luas, besarnya jendela membuat sinar mentari mampu menerangi seluruh ruangan.
Yang ada di ruangan itu hanyalah sebuah ranjang yang sedang ia tiduri, sebuah
meja dengan vas bunga dan teko teh di atasnya, dan sebuah sofa yang dihiasi
bantal berwarna hijau, kontras dengan warna putih yang menyelimuti sekitar.
Begitu ia beranjak dari tempat tidurnya, seorang gadis berseragam SMA berjalan
masuk membawa nampan penuh makanan.
“Ibu sudah
bangun?”, Tanya gadis itu dengan seyuman lembut mengembang di bibirnya.
Wanita tua
itu hanya terdiam mendengar pertanyaan itu. Ia menatap gadis itu lekat-lekat
dari ujung kepala hingga ujung kaki.
‘Siapa…
Gadis itu?’ Batinnya.
Gadis itu
berjalan mendekati meja kecil di sisi tempat tidur dan meletakkan nampan yang
tadi di atasnya. Wanita tua itu memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan
seksama. Begitu banyak tanya yang berkelebat dalam hatinya, namun entah kenapa
bibirnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun.
“Ini
sarapan ibu. Ayo dimakan sekarang, nanti keburu dingin.” Tutur gadis itu
lembut.
Wanita tua
tadi masih menatapnya dengan bingung. Meskipun begitu, sang gadis tetap
tersenyum lembut seakan tak menyadari tatapan wanita itu. Gadis itu memberi isyarat
pada wanita tua itu untuk duduk di tempat tidur, kemudian ia sendiri mengambil
kursi tak jauh dari tempat itu lalu mendudukinya. Melihat si wanita tua tidak
melakukan apa-apa, ia kembali bertanya,
“Ibu ingin
makan sendiri? Apa perlu saya suapi?” Tanya gadis itu disertai tawa lirih.
Wanita itu
masih tetap terdiam, namun akhirnya ia memutuskan untuk duduk dan meraih sendok
di atas nampan tadi. Perlahan-lahan wanita itu mengunyah makanan yang ada di
mulutnya. Sesekali ia melirik kearah gadis tadi, dan ia menyadari senyum
lembutnya sudah tak lagi berkembang. Gadis itu menatap kosong kearah secangkir
teh di sebelah nampan. Wanita tua itu pun ikut menatap cangkir teh itu. Wangi
melatinya seakan mengingatkannya akan sesuatu, namun ia tidak tahu apa.
Wanginya terasa begitu… ‘Dekat’…
“Oh,
astaga! Maaf Bu, saya harus pergi!” Kata gadis itu sambil beranjak dari
kursinya begitu melihat kearah jam. Gadis itu berlari ke pintu, namun ia
berhenti sebentar lalu menengok kebelakang.
“Assalamu’alaikum…”
Ucapnya, kemudian melanjutkan larinya keluar.
“…
Waalaikum salam…” Jawab wanita tua itu akhirnya. Ia berhenti mengunyah
makanannya, menatap ke arah pintu yang setengah tertutup.
‘Siapa
gadis tadi? … Dan dimana ini?’ Tanyanya dalam hati.
Ditaruhnya
kembali sendok di tangannya ke atas nampan. Begitu banyak Tanya yang berkelebat
menghancurkan nafsu makannya. Ia berdiri dan melihat ke luar jendela. Nampaknya
ia berada di lantai 2 sebuah gedung. Di bawah sana ia melihat taman kecil
dengan beberapa orang berpakaian seragam berjalan-jalan. Taman itu dikelilingi
oleh kampu-lampu kecil dan diapit oleh koridor sempit. Ada satu jalan kecil di
tengah taman itu, dan seorang gadis sedang berlari melewatinya. Gadis yang tadi
membawakannya sarapan. Gadis itu berhenti berlari dan menengok ke atas, ke arah
wanita itu. Gadis itu tersenyum lalu melambai-lambaikan tangannya, kemudian ia
kembali berlari.
Wanita tua
itu hanya menatap punggung gadis itu yang semakin jauh dari penglihatannya.
Wajah tersenyum gadis itu masih terbayang di pikirannya. Suaranya, caranya
berbicara, posturnya yang tidak begitu tinggi dan tidak juga pendek, rambut
panjangnya yang lurus dan jatuh sempurna di bahunya, juga tatapan kosongnya
waktu itu. Semuanya terbayang. Semuanya sangat asing, namun entah kenapa…
Terasa begitu ‘Dekat’.
Ia sendiri
tidak mengerti perasaannya. Kenapa gadis itu begitu mengganggu pikirannya? Ah,
mungkin saja karena gadis yang tidak dikenalinya itu datang di pagi hari,
membawakan sarapan dan memanggilnya… ‘Ibu’.
“Ibu… ?”,
Bisiknya.
Kapan ia
pernah mendengar panggilan itu?
Perlahan ia
hampiri meja kecil tadi. Ia tarik lacinya dan menemukan sebuah cermin kecil
didalamnya. Ia ambil cermin itu, ia menatap bayangan yang terpantul disana.
Wajahnya. Wajah bulat yang sudah mulai keriput, dihiasi rambut lurus sebahu.
Wajah yang terlihat tua.
‘Sejak
kapan aku menjadi terlihat tua? … Rasanya kemarin aku…’
Pikirannya
membeku seketika. ‘Kemarin’? Ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi ‘kemarin’.
Kalau dipikir, ia pun tidak ingat kenapa ia bisa terbangun di tempat ini. Ia
pun tidak ingat siapa gadis tadi.
Sakit
kepala yang tiba-tiba muncul memaksa tubuhnya untuk duduk. Ia merasa ada
sesuatu yang hilang. Sesuatu yang ‘dekat’, tapi ia tidak tahu apa itu. Sebuah
melodi terlantun dalam benaknya, suatu nyanyian yang sangat lembut. Ia
lantunkan melodi itu. Setiap nada yang ia nyanyikan membuka sesuatu dalam dirinya,
menampilkan gambar-gambar di dalam pikirannya…
“Ibu!”
“Dinda hari ini ceria sekali, ya?”
“Hari ini hari yang baik untuk
jalan-jalan, ya ‘kan?”
Seakan
tersambar petir, mata wanita tua itu terbelalak saat mendengar suara-suara
dalam kepalanya.
“Dinda…”,
Bisiknya.
Ia buka
lagi laci meja kecil itu. Penuh dengan benda-benda kecil. Namun ada beberapa
benda yang menarik perhatiannya. Sebuah album foto dan sebuah catatan kecil
yang manis. Ia buka album itu. Ada wajahnya disana, bersama wajah-wajah lain
yang asing. Halaman demi halaman ia buka, hampir selalu ada dirinya, wajahnya
yang masih bersih dari kerutan. Dan di halaman terakhir, ada potret dirinya,
bersama seorang gadis berumur belasan tahun yang tersenyum bahagia. Di
atas foto itu tertulis, “Dinda sayang ibu”.
“Dinda…”
Lagi-lagi
nama itu muncul di benaknya. Mungkinkah…
Dibukanya
catatan kecil yang ia temukan. Catatan itu cukup lusuh, mungkin sudah berapa
lama tidak dibuka. Catatan itu berisi tulisan tangan yang rapi, tentang
keseharian seseorang. Catatan itu adalah diary
milik Dinda.
Banyak hal
yang tertulis disana. Mulai dari Dinda yang baru akan masuk SMP, bertemu
teman-teman baru, jalan-jalan bersama keluarga, saat ia sedih… Saat ia sedih,
ia bercerita pada ibunya. Ibunya pasti akan mendekapnya erat sambil membelai
lembut rambutnya dan memberikan nasihat-nasihat padanya. Kemudian yang paling
ia sukai adalah saat ibunya menyanyikan sebuah lagu berjudul…
“Memoria…”
Tubuhnya
bergetar. Ia mengingatnya, Ia mengingat lagu itu. Ia nyanyikan lagu itu lagi.
Ia nyanyikan lagu itu berulang-ulang.
“Dinda…
Dinda…”
Ia masih
menyanyikannya. Ia terus menyanyikannya sampai ia merasa kesal. Kenapa ia dapat
mengingat lagu itu? Tapi kenapa ia tidak bisa mengingat yang lainnya? Kenapa ia
tak tahu apa yang terjadi ‘kemarin’? Kenapa ia tak ingat alas an ia terbangun
di tempat ini? Tempat yang sepi, yang tak ia kenali? Kenapa… Kenapa ia tak
ingat siapa itu ‘Dinda’?
“Dinda sayang ibu!”
Suara itu
kembali terngiang di telinganya. Sebuah wajah polos dengan senyum bahagia
terlukis dalam pikirannya. Senyuman seorang gadis yang sangat ia sayangi…
“Dinda…
Dinda putriku…”
Tetes air
mata membasahi pipinya. Rasa rindu yang tak tertahankan menusuk-nusuk dadanya.
Kembali ia buka halaman-halaman diary
itu.
Ibu bilang hari ini kita akan berkunjung
ke rumah tante Nisa. Sebenarnya aku agak malas karena di tempat tante
ngebosenin. Yang ada Cuma anak kecil dan TV-nya pasti dinyalain untuk nonton
kartun doang! Tapi aku harus ikut, soalnnya Ayah dan Kakak juga mau ikut. Ya
udah deh!
12 Juni 2008
Ah, sudah hampir sebulan aku tidak menulis
disini lagi. Itu artinya sudah hamper sebulan sejak kecelakaan itu ya? Waktu
sangat cepat berlalu ya. Tapi ibu sampai sekarang belum sadarkan diri. Aku
harap ibu segera bangun, aku nggak ingin ditinggal ibu. Ayah sudah tiada. Apa
yang akan terjadi padaku dan kakak?
9 Juli 2008
Akhirnya ibu siuman. Tapi ada sesuatu yang
aneh dengannya. Ibu tidak mengatakan apa-apa saat melihat aku dan kakak.
Matanya kosong, seakan tidak mengenal kami. Dokter bilang ibu amnesia. Oh,
tuhan, aku bersyukur ibu sudah siuman, namun jika keadaan ibu seperti ini, aku
nggak tahu harus apa lagi…
11 Juli 2008
Lagi-lagi aku absen menulis diary. Aku dan
kakakku cukup shock. Amnesia yang dialami ibuku bukan amnesia biasa, tapi ‘anterograde amnesia’. Dokter bilang ibuku akan melupakan kejadian hari ini pada keesokan
hari, dan begitu seterusnya. Aku benar-benar sedih. Setiap harinya aku berkata,
“Ibu, ini Dinda”, “Ibu, ini anakmu, Dinda!”. Namun ternyata itu percuma. Besok,
besok lusa dan seterusnya, ibu akan terus melupakan aku. Kakak pun sudah lelah
mengingatkan. Ia bilang, “biarkan saja, kasihan Ibu.”. Tapi aku nggak ingin Ibu
melupakan aku…
21 Juli 2008
Itulah
halaman terakhir diary ini.
Sepertinya ia tidak lagi melanjutkan tulisannya.
Wanita tua
itu terisak. Ia terus membuka-buka catatan kecil itu, berharap ada tulisan lain
dari putrinya. Lalu ia menemukan satu kalimat di halaman terakhir.
“Ibu maafkan Dinda. Dinda juga lelah, sama
seperti kakak. Tapi Dinda akan selalu sayang Ibu, karena Dinda tahu meskipun
keadaan Ibu seperti ini, Ibu selalu menyayangi kami.”
Tetes air
mata itu seakan tidak mau berhenti. Ia kembali menyanyikan lagu yang ia ingat
itu, namun ia justru semakin kesal…
“Dinda…
Dinda… Dinda!!” Jeritnya.
Seorang suster
datang menghampirinya.
“Bu, ada
apa bu?”
“Dinda… Di mana
Dinda? Di mana putriku? Aku ingin bertemu sekarang!”
“Ibu,
tenangkan diri anda dulu…” Suster itu berusaha menenangkan wanita tua itu.
“Menjauh
dariku! Aku ingin bertemu putriku sekarang!!” Jerit wanita tua itu.
Tak lama
suster-suster lain datang dan berusaha menenangkannya, namun wanita itu tetap
menjerit dan berontak. Ia meloncat dari tempat tidurnya dan berlari keluar dari
kamar.
Ia berlari
sekencang yang ia bisa, sambil mendekap diary
kecil milik putrinya. Ia berlari menyusuri koridor-koridor sempit yang penuh
orang-orang, tak peduli banyak orang yang mengejarnya di belakang. Ia tak
peduli kalau ia tersesat, Ia tak peduli apa-apa lagi, yang ia pedulikan
hanyalah keinginannya untuk bertemu sang putri tercinta.
Lalu tanpa
ia sadari, Angin segar berhembus melewati tubuhnya. Ia sudah sampai di luar
gedung, dan ia tengah berdiri di tengah jalan. Lalu ia terbangun dari
lamunannya saat suara klakson yang keras merambat masuk ke telinganya.
*
* *
Dingin.
Udara
dingin menggelitik hidungnya, menusuk tulangnya. Ia membuka matanya. Ternyata
jendelanya belum ditutup, padahal langit sudah gelap… Sudah malam?
Ia melihat
di sampingnya, seorang gadis tertidur di sisi ranjang yang sedang ia tiduri.
Rambut panjangnya yang lurus jatuh menutupi wajahnya.
“Dinda…”
Bisiknya sambil membelai lembut kepala gadis itu. Ia sisihkan rambut dari wajah
gadis itu agar ia dapat melihat wajah yang sangat ia rindukan.
“Dinda…
Kamu pasti lelah ya nak? Setiap hari mengurusi Ibu yang… Kondisinya seperti
ini?” Tuturnya lirih.
Mata gadis
itu perlahan terbuka, menatap lembut ke arah sang Ibunda.
“Ibu…?”
Wanita tua
itu tersenyum lembut dengan mata berkaca-kaca, masih membelai kepala gadis itu.
“Ibu selalu
sayang Dinda…” Tutur wanita itu lembut, diringi tetesan jernih dari matanya.
Kemudian ia
menyenandungkan melodi itu. Selagi ia masih ingat, selagi hari esok belum
datang, ia ingin memberikan banyak kasih saying yang tak sempat ia beri selama
ini. Sudah berapa lama rasa sayangnya ini terkubur? Sudah berapa tahun? Dan
selama itu, putrinya terus berada di sisinya. Setiap hari ia dihadapkan oleh
kenyataan bahwa ia telah dilupakan oleh ibunya sendiri. Itu pasti membuatnya
sakit. Sangat, sangat sakit.
Kemudian
gadis itu ikut menyanyikannya, menyanyikan melodi indah yang menjadi
satu-satunya jembatan penghubung mereka dengan masa lalu yang indah, yang tak
akan kembali lagi. Diiringi dengan tetesan air dari dua pasang bola mata,
menjadikan lagu itu lebih istimewa dibanding lagu-lagu lainnya…
Memoria, melodi yang tak terlupakan…
~ F i n ~
Langganan:
Komentar (Atom)